
Merangin, 6 Februari 2026 — Pemerintah Provinsi Jambi menggelar kegiatan Gerakan Tanam Perdana dan Doa Turun Baumo serta Tanam Padi Ramah Lingkungan dalam rangka Progam BioCF-ISFL di areal persawahan kelompok Tani Usaha Baru, Desa Seling, Kecamatan Tabir, Kabupaten Meranging, Jumat (6/2). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya musim tanam sekaligus penguatan komitmen pertanian berkelanjutan dan rendah emisi di Provinsi Jambi.
Acara dihadiri Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, unsur Forkopimda Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin, perwakilan kementerian, perangkat daerah, penyuluh pertanian, serta para petani. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Jambi merupakan salah satu provinsi pelaksana BioCF-ISFL yang diarahkan untuk mendukung pembangunan rendah emisi melalui penguatan tata kelola serta praktik berkelanjutan di sektor kehutanan, pertanian, dan penggunaan lahan.
Menurut Gubernur, saat ini pelaksanaan BioCF-ISFL di Jambi masih berada pada fase pra-investasi yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasiiitas pemerintah daerah dan masyarakat, penyelarasan kebijakan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Ia juga menekankan pentingnya pertanian ramah lingkungan sebagai masa depan sektor pertanian karena mampu menekan biaya produksi, mengurangi ketergantungan bahan kimia, dan menjaga kesuburan tanah.
Kegiatan Doa Turun Baumo yang menjadi bagian dari rangkaian acara turut diangkat sebagai wujud kearifan lokal masyarakat dalam menyambut musim tanam, mencerminkan keseimbangan antara ikhtiar, doa, dan keharmonisan dengan alam. Pemerintah berharap pendekatan budaya ini dapat memperkuat semangat dan partisipasi petani dalam menerapkan praktik budidaya berkelanjutan.
Berdasarkan laporan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, gerakan tanam perdana ini mencakup bantuan benih padi untuk lahan seluas 30 hektare bagi Kelompok Tani Usaha Baru Desa Seling. Program BioCF-ISFL sendiri telah berjalan sejak 2022 dan tahun 2026 menjadi tahap penutup fase pra-investasi sebelum masuk ke fase pembayaran berbasis kinerja. Program ini bertujuan mendorong pengelolaan lahan berkelanjutan, menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi deforestasi, dan meningkatkan taraf hidup petani.
Selain benih padi, turut diserahkan berbagai bantuan sarana produksi kepada sejumlah kelompok tani di Kabupaten Merangin, antara lain motor roda tiga, mesin APPO (alat pengolah pupuk organik), benih rumput pakan ternak unggul, knapsack elektrik, serta dukungan peningkatan kapasitas pengolahan biopestisida dan pupuk organik cair. Bantuan juga disalurkan melaluio perangkat daerah lain seperti Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, dan KPH sebagai bagian dari paket program BioCF-ISFL fase pra-investasi.
Gubernur juga menyoroti potensi luas sawah di Dssa Seling yang mencapai sekitar 171 hektare dan dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai lumbung pangan daerah. Kabupaten Merangin sendiri masuk dalam kawasan swasembada pangan sesuai arah pembangunan kewilayahan Provinsi Jambi. Ia menambahkan, peningkatan Nilai Tukar Petani Jambi pada Januari 2026 menjadi 173,36 menunjukkan tren perbaikan kesejahteraan petani dan menjadi modal optimisme menghadapi musim tanam tahun ini.
Pemerintah Provinsi Jambi berharap gerakan tanam perdana ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi titik awal musim tanam yang produktif, ramah lingkungan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan daerah.
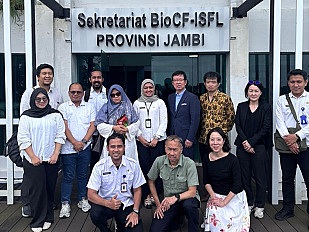
IGES, lembaga di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, memperkenalkan teknologi sabun pemadam kebakaran hutan dan lahan gambut yang dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemadaman serta menekan emisi karbon. Teknologi ini telah digunakan di Jepang sejak 2007 dan mulai diuji coba di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, sejak 2011
Uji coba di air gambut Kalimantan Tengah dilakukan secara bertahap mulai 2016 dan dikembangkan kembali pada 2018. Pada uji coba di Kalimantan Tengah tahun 2013, IGES menunjukkan hasil signifikan. Penggunaan sabun pemadam ini mampu mempercepat proses pemadaman hingga sepertiga lebih cepat dengan kebutuhan air yang lebih sedikit dibandingkan metode konvensional.
Demonstrasi skala besar juga telah dilakukan di hadapan para pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan pengalaman BPDP setempat, air yang dicampur sabun dapat menembus lapisan lahan gambut hingga kedalaman sekitar empat meter, sehingga membantu memadamkan api di lapisan bawah.
Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, IGES menyampaikan rencana perluasan uji coba ke Provinsi Jambi. Jambi dinilai memiliki karakteristik lahan gambut yang sering mengalamai kebakaran setiap tahun, sehingga cocok sebagai lokasi pengujian lanjutan. Uji coba direncanakan berlangsung pada musim kemarau, yakni antara Juni hingga Oktober, dengan jumlah sampel terbatas.
Selain mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, teknologi ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon dan skema karbon kredit. IGES menyatakan bahwa produk tahap awal akan diekspor dari Jepang, namun apabila permintaan Indonesia meningkat, tidak menutup kemungkinan akan dibangun pabrik di Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
Peluang kerja sama juga terbuka tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan sektor swasta, khususnya perusahaan perkebunan yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi terhadap teknologi pemadaman kebakaran lahan.
-thumb.jpg )
Jambi, 22 Desember 2025 – Perubahan Iklim kini bukan lagi isu global yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Dampaknya nyata, mulai dari cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman terhadap sumber penghidupan masyarakat. Di tengah tantangan tersebut, Provinsi Jambi tampil sebagai salah satu daerah yang serius menata langkah menuju pembangunan rendah karbon melalui penguatan tata kelola hutan dan karbon.
Komitmen ini tercermin dalam pengembangan berbagai inisiatif pengendalian emisi gas rumah kaca, mulai dari penguatan arsitektur REDD+, penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), hingga pelaksanaan Program BioCarbon Fund-Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL) yang didukung Bank Dunia.
Modal Alam dan Komitmen Daerah
Dengan Ekosistem hutan yang lengkap—mulai dari hutan hujan dataran rendah, pegunungan, hingga kawasan gambut dan mangrove—Jambi memliki posisi strategis dalam upaya penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Lebih dari 40 persen wilayah provinsi ini masih berupa kawasan hutan, termasuk empat taman nasional yang menjadi habitat satwa kunci Sumatra.
Pemerintah Provinsi Jambi juga dinilai memiliki fondasi kelembagaan yang relatif kuat. Kelembagaan REDD+ telah terbentuk, kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat, serta skema perhutanan sosial dikembangkan untuk mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
"Upaya menurunkan emisi tidak bisa dilepaskan dari perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, aksi iklim harus terintegrasi dengan ekonomi, tata ruang, dan kesejahteraan masyarakat," menjadi salah satu benang merah yang mengemuka dalam berbagai pemaparan.
BioCF-ISFL: Insentif untuk Menjaga Hutan
Melalui Program BioCF-ISFL, Provinsi Jambi menargetkan penurunan emisi hingga 10 juta ton CO2e. Program ini mencakup intervensi di berbagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perhutanan sosial, lahan gambut, hingga wilayah non hutan. Tidak hanya fokus pada penurunan emisi, BioCF-ISFL juga diarahkan untuk mendorong kegiatan produktif berkelanjutan seperti agroforestri, pertanian ramah lingkungan, dan restorasi lahan terdegredasi.
Bagi daerah, skema ini menjadi peluang strategis untuk mengaitkan perlindungan lingkungan dengan manfaat ekonomi langsung, sekaligus mendukung target besar Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Nesting Karbon, Menyatukan Banyak Inisiatif
Seiring berkembangnya proyek-proyek karbon di tingkat tapak—baik berbasis komunitas, perhutanan sosial, maupun konsesi—tantangan baru pun muncul. Tanpa mekanisme yang jelas, risiko penghitungan ganda, klaim ganda, hingga konflik kepentingan menjadi terelakkan.
Di sinilah nesting karbon menjadi krusial. Nesting adalah mekanisme untuk menyelaraskan proyek-proyek karbon dengan program yurisdiksi provinsi dan kebijakan nasional, sehingga seluruh penurunan emisi dapat dicatat, diverifikasi, dan dimanfaatkan secara sah.
Berbagai pendekatan nesting dibahas, mulai dari integrasi penuh (fully nested), sebagian (parially nested), hingga opsi transisi yang memberi ruang bagi proyek tetap berjalan sambil menyesuaikan baseline dan sistem MRV dengan yurisdiksi.
Standar internasional seperti Plan Vivo menekankan peran petani kecil dan masyarakat sebagai pusat kegiatan, sementara ART-TREES membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan kredit karbon yurisdiksi yang dapat diperdagangkan di pasar sukarela maupun regulasi. Fleksibilitas ini memberi ruang bagi Jambi untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakter wilayahnya.
Masyarakat di Pusat Tata Kelola
Isu penting lainnya adalah bagaimana memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek dalam ekonomi karbon. Pendekatan polycentric governance menegaskan bahwa pengambilan keputusan harus melibatkan banyak aktor di berbagai tingkat, dengan masyarakat sebagai titik temu utama.
Prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC), pembagian manfaat yang adil, safeguards sosial dan lingkungan, serta mekanisme pengauan menjadi elemen kunci agar kebijakan karbon tidak menciptakan ketimpangan baru.
"Menjaga hutan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan," menjadi pesan kuat yang terus ditekankan.
Menuju Pasar Karbon yang Berintegritas
Dengan terbitnya Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon dan aturan turunannya, Indonesia memasuki babak baru pengelolaan emisi. Perdagangan karbon tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.
Bagi Provinsi Jambi, kesiapan memasuki pasar karbon menuntuk kejelasan hak atas karbon, sistem MRV yang kredibel, serta koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Tantangan tersebut sekaligus membuka peluang untuk menjadikan Jambi sebagai model nasional tata kelola karbon berintegritas.
Ke depan, keberhasilan Jambi tidak hanya diukur dari besarnya emisi yang diturunkan atau nilai karbon yang diperdagangkan, tetapi dari kemampuannya menyeimbangkan perlindungan hituan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonom hijau yang berkalnjutan.
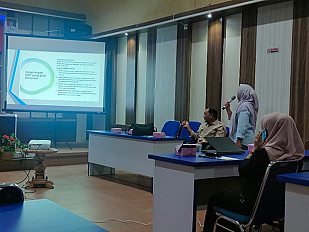
Sungai Penuh/Kerinci – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fase Result Based Payment (RBP) Program BioCarbon Fund–Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL), telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada 14–17 Desember 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan terkait konsep pembayaran berbasis hasil (Result Based Payment), mulai dari tujuan, mekanisme pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan yang harus dicapai agar pembayaran dapat direalisasikan. Selain itu, sosialisasi juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah yang terlibata dalam program BioCF-ISFL.
Sosialisasi pertama dilaksanakan di Kota Sungai Penuh pada Senin, 15 Desember 2025, bertempat di Bappeda Kota Sungai Penuh, dan dilanjutkan di Kabupaten Kerinci pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di Bappeda Kabupaten Kerinci. Kedua kegiatan dimulai pada pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam diskusi di Kota Sungai Penuh, dibahas antara lain mengenai dokumen safeguard sesuai Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022, termasuk alur pengajuan proposal masyarakat ke sekretariat safeguard serta format Surat Pernyatanaan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang mengacu pada standar Bank Dunia. Selain itu, disampaikan pula pentingnya pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) melalui SK Kepala Daerah, dengan menyesuaikan kebutuhan daaerah dan memastikan seluruh pihak yang berkompeten terlibat secara inklusif.
Diskusi juga menyoroti perbedaan antara desa penerima alokasi kinerja dan desa penerima alokasi insentif sosial ekonomi. Desa alokasi kinerja ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan penurunan emisi oleh tim Measurement, Analysis, and Reporting (MAR), sedangkan desa alokasi insentif sosial ekonomi ditentukan berdasarkan hasil olahan data Kabupaten dan Badan Informasi Spasial (BIG) yang kemudian dibahas bersama para pemangku kepentingan sebelum diusulkan ke tingkat provinsi.
Sementara itu, pada sosialisasi di Kabupaten Kerinci, pemerintah daerah diharapkan segera membentuk Tim Pokja Kabupaten dan menyerahkan draf pembentukannya kepada SNPMU. Keanggotaan Tim Pokja dianjurkan berbasis nama, bukan jabatan, agar dapat berkelanjutan dalam jangka panjgan. Selain itu, dibahas pula mekanisme alokasi dana untuk Perhutanan Sosial (PS) berdasarkan luasan dan kinerja penurunan emisi yang dihitung oleh tim MAR.
Terkait insentif sosial ekonomi, Kabupaten Kerinci didorong untuk segera mengajukan pendaftaran desa calon penerima manfaat, mengingat batas akhir penetapan penerima dana RBP adalah 31 Desember 2025. Setelah tanggal tersebut, desa yang belum terdaftar dipastikan tidak dapat memperoleh manfaat pembayaran berbasis hasil.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci diharapkan segera membentuk Tim Pokja yang mencakup bidang perhitungan emisi gas rumah kaca, safeguard, mekanisme pembagian manfaat, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, potensi konflik batas desa akan dibahas lebih lanjut di tingkat provinsi. Daftar desa penerima insentif sosial ekonomi akan ditetapkan melalui mekanisme pembahasan di tingkat kabupaten dan disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama, partisipasi aktif masyarakat meningkat, serta pelaksanaan Program BioCF ISFL dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Jambi – Program BioCarbon Fund–Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL) di Provinsi Jambi terus menunjukkan perkembangan signifikan sebagai upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Program yang didukung Bank Dunia ini menerapkan skema Result Based Payment (RBP), yakni pembayaran yang hanya diberikan atas capaian nyata penurunan emisi yang telah diverifikasi.
Dalam pemaparan yang disampaikan Rahmad Mulyadi, dijelaskan bahwa Program BioCF-ISFL dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pra-investasi, dan pembayaran berbasis kinerja. Pada tahap persiapan yang berlangsung pada 2019–2021, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun berbagai dokumen penting seperti Emission Reduction Program Document (ERPD), dokumen safeguard, serta membentuk kelembagaan dan menetapkan empat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai wilayah intervensi.
Memasuki tahap pra-investasi periode 2021–2025, Jambi menerima hibah dari Bank Dunia sebesar kurang lebih USD 13,5 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan di tingkat KPH dan organisasi perangkat daerah (OPD), dengan fokus pada penciptaan kondisi pendukung penurunan emisi. Pada fase ini, pembayaran kinerja belum dilakukan karena masih bersifat persiapan lapangan.
Sementara itu, pada tahap RBP yang mencakup periode 2020–2026, Provinsi Jambi ditargetkan menurunkan emisi sebesar 10 juta ton CO₂e, dengan nilai pembayaran sebesar USD 7 per ton. Namun hingga saat ini, pembayaran tersebut belum dapat direalisasikan karena Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) masih dalam proses penandatanganan.
Dari sisi implementasi, sosialisasi serta proses Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau Padiatapa telah dilakukan di 230 desa. Seluruh desa menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi dalam program tanpa adanya paksaan. Dokumen prasyarat RBP juga telah dinyatakan final pada awal 2025.
Dio mulyanda menjelaskan bahwa penghitungan penurunan emisi dilakukan melalui sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) atau Measurement, Analysis, and Reporting (MAR), dengan membandingkan emisi aktual terhadap emisi baseline historis. Hasil perhitungan ini menjadi dasar klaim pembayaran RBP. Entitas yang berhak memperoleh manfaat antara lain desa, KPH, taman nasional, pemegang izin, perhutanan sosial, sereta pemerintah daerah yang memiliki mandat pengelolaan kawasan.
Terkait pembagian manfaat, Hendra Admaja menyampaikan bahwa mekanisme tersebut diatur dalam dokumen Benefit Sharing Mechanism (BSM) dan mengacu pada regulasi nasional. Alokasi manfaat terbesar diberikan berdasarkan kinerja penurunan emisi, namun desa yang tidak masuk kategori kinerja tetap berpeluang menerima dukungan melalui alokasi sosial-ekonomi.
Aspek perlindungan sosial dan lingkungan juga menjadi perhatian utama. Taufik menjelaskan bahwa safeguard REDD+ diterapkan untuk meminimalkan risiko sosial dan lingkungan, seperti konflik lahan, risiko kesehatan, hingga isu kesetaraan gender. Safeguard mencakup penapisan dokumen lingkungan, pengelolaan keluhan melalui Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), serta Monitoring dan Evaluasi secara berkala.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menanyakan peluang penambahan desa penerima manfaat. Narasumber mengaskan bawha penambahan desa penerima manfaat. Narasumber mengaskan bahwa penambahan desa dimungkinkan selama berada di wilayah intervensi dan memenuhi kriteria program. Isu monitoring, evaluasi, dan audit juga menjadi sorotan, dengan penegasan bahwa pengawasan akan dilakukan secara berlapis, termasuk audit melalui skema lembaga perantara (Lemtara) yang mengacu pada praktik pendanaan iklim internasional.
Sebagai kesimpulan, Program BioCF-ISFL dinilai memberikan peluang manfaat yang luas bagi desa dan pemangku kepentingan daerah di Jambi.Keberhasilan program sangat bergantung pada penandatangan ERPA, penguatan kapasitas kelembagaaan melalui bimbingan teknis, serta peran aktif Pokja Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memastikan implementasi program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Tanjung Jabung Barat – Dalamm rangka pelaksanaan sosialisasi Fase Result Based Payment (RBP) Program BioCarbon Fund – Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL), tim pelaksana melakukan kunjungan dinas ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 Desember 2025 bertempat di Kantor Bappeda Tanjung Jabung Barat.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan [erkembangan terbaru Program BioCF-ISFL,khususnya terkait tahapan RBP, kesiapan pemerintah daerah dalam penyusunan proposal RBP sesuai Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP), serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi daerah dalam implementasi program.
Dalam kegiatan sosialisasi, peserta mendapatkan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan BioCF-ISFL, status Emission Reduction Payment Agreement (ERPA), serta metode perhitungan emisi, termasuk contoh perhitungan faktor emisi akibat perubahan tutupan hutan. Selain itu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan telah memahami alur Measurement, Reporting, and Verifiaction (MAR) yang meliputi pengumpulan data kebakaran dan deforestasi, analisis spasial, hingga penyusunan laporan penurunan emisi.
Mekanisme pembagian manfaaat yang bersifat khusus bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu penyaluran manfaat melalui transfer langsung ke desa oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), juga disampaikan dan diterima dengan baik oleh para peserta. Sosialisasi ini turut menjelaskan kelompok penerima manfaat, termasuk perusahaan pemegang HGU dan petani swadaya dialokasikan sebagai buffer.
Selain aspek teknis dan pembagian manfaat, instrumen safeguard program, mekanisme Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), serta daftar kegiatan yang dilarang (negative list) dipaparkan secara komprehensif kepada perwakilan OPD, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait.
Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi RBP BioCF-ISFL di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlangsung dengan baik dan berhasil meningkatkan pemahaman para pihak terhadap alur MAR, mekanisme pembagian manfaat, serta ketentuan penyaluran dana langsung dari BPDLH ke desa. Meskipun masih terdapat beberapa desa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut dalam penyusunan proposal dan pengumpulan data dasar, kegiatan ini dinilai mampu memperkuat kesiapan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menghadapi fase RBP dan mendukung implementasi program di tingkat kabupaten.

Batanghari – Program BioCarbon Fund–Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BiOCF-ISFL) di Provinsi Jambi terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak dimulai pada 2019. Program ini dirancang dalam tiga tahapan, yakni persiapan (2019-2021), pra-investasi (2021-2025), dan pembayaran berbasi kinerja atau Result Based Payment (RBP) pada periode 2020-2026.
Dalam diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, disampaikan bahwa hingga saat ini telah dilakukan proses Free, Prior, dan Informed Consent (FPIC) atau Padiatapa di 230 desa/keseluruhan yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Seluruh desa tersebut menyatakan kesediaan mengikuti Program BioCF-ISFL tanpa unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan.
Selain itu, dokumen prasyarat penting seperti Emission Reduction Program Document (EROD), Benefit Sharing Mechanism (BSM), Safeguard, dan Environmental and Social Due Diligance (ESDD) telah disusun dan difinalisasikan sebagai dasra menuju Perjanjian Pembayaran Penurunan Emisi (Emission Reduction Payment Agreement/ERPA). Namun demikian, hingga saat ini ERPA masih menunggu penandatanganan.
Dalam mekanisme RBP, kinerja penurunan emisi diukur melalui sistem MRV atau Measurement, Reporting, and Verification (dikenal sebagai MAR di Jambi), yang membandingkan emisi aktual tahun 2020-2022 dengan emisi baseline berdasarkan data historis periode 2006-2018. Penurunan emisi dinyatakan tercapai apabila emisi aktual leih rendah dari emisi baseline.
Terkait pembagian manfaat, terdapat lima kelompok penerima manfaat, yaitu pemerintah, swasta, komunitas/masyarakat/desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi. Alokasi terbesar diberikan kepada masyarakat dan desa, termasuk kelompok Perhutanan Sosial, KKPH, unit konservasi, serta pelaku usaha yang berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi. Bentuk manfaat terdiri dari manfaat moneter (tunai dan non-moneter (in-kind), dengan komposisi 40 persen dialokasikan untuk kegiatan penuruna emisi dan 60 persen untuk program sosial ekonomi.
Di kabupaten Batanghari, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kehutanan. KPH bertugas melakukan koordinasi lintas sektor, menyiapkan merekomendasikan proposal, serta mempersiapkan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan safeguard. KPH juga menjadi bagian dari kelompok kerja (Pokja) dan salah satu penerima manfaat program.
Program ini melibatkan sembilan desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Mersa, Muaro Sebo Ulu, dan Muaro Bulian. Desa-desa yang memiliki kawasan hutan maupun yang tidak memiliki hutan tetap didorong untuk bertasipasi dalam pengelolaan hutan secara inklusif.
Pemerintah Kabupaten Batanghari menunjukkan komitmen kuat dengan mengintegrasikan program BioCF-ISFL ke dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari strategi penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan kesiapan provinsi dan kabupaten, Program BioCF-ISFL diharapan mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Program BioCarbon Fund – Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL) melaksanakan sosialisasi Fase Result Based Payment (RBP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini berlangsung pada 12 Desember 2025 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kunjungan dinas ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan terkini Program BioCF-ISFL, khususnya terkait tahapan RBP, status Emission Reduction Payment Agreement (ERPA), serta pengurangan target emisi. Selain itu, kegiatan ini juga difokuskan pada penyampaian kesiapan pemerintah daerah dalam penyusunan proposal RBP sesuai dengan Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP), sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di tingkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut, pemaparan mengenai tahapan BioCF-ISFL, perhitungan emisi, peneteapan baseline, aktivitas perubahan penggunaan lahan, serta peran Measurement, Analysis, Reporting, and Verification (MAR/MRV) dalam verifikasi penurunan emisi dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh para peserta. Mekanisme pembagian manfaat juga dijelaskan secara rinci, termasuk alokasi bagi pemerintah, desa, perhutanan sosial, sektor swasta, LSM, dan perguruan tinggi, serta kewajiban alokasi minimal 10 persen untuk Gender Equality and Social Inclusion (GESI).
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakn telah memahami tugas dan perannya dalam melakukan penapisan proposal RBP sesuai BSP serta pentingnya sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah. Selain itu, berbagai isu lokal turut dibahas, seperti ketersediaan dan validitas data tutupan lahan, status HGU perkebunan, serta kesiapan entitas perhutanan sosial sebagai calaon penerima manfaat program.
Secara keseluruhan, sosialisasi RBP BioCF-ISFL di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjalan dengan baik dan dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman pemerintah daerah. Kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah sebagai langkah awal untuk mempercepat penyusunan proposal RBP yang sesuai dengan ketentuan BSP. Ke depan, kegiatan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan pendampingan teknis lanjutan guna mengatasi kendala data dan kesiapan entitas di daerah

Muaro Jambi — Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Fase Result Based Payment (RBP) Program BioCarbond Fund—Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) ke kabupaten/kota di Provinsi Jambi, tim pelaksana melakukan kunjungan dinas ke kabupaten/kota di Muaro Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 8 Desember 2025 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muaro Jambi.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan perkebangan terkini Program BioCF-ISFL, khususnya terkait tahapan RBP, kesiapan pemerintah daerah dalam penyusunan proposal RBP sesuai Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP), serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di tingkat kabupaten.
Dalam kegiatan sosialisasi, peserta mendapatkan pemaparan menyeluruh mengenai tahapan Program BioCF-ISFL yang meliputi fase persiapan, pra-investasi, hingga RBP. Selain itu, disampaikan pula status dokumen pendukung utama seperti Emission Reduction Program Document (ERPD), Benefit Sharing Mechanism (BSM), Safeguard, dan Environmental and Social Due Diligence (ESDD).
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga memperoleh pemahaman terkait perubahan target Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) yang kini ditetapkan sebesar 10 juta ton CO2e. Peserta sosialisasi menerima penjelasan rinci mengenai mekanisme penyusunan proposal RBP, proses penapisan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten, serta pentingnya sinkronisasi program dengan RPJM Desa dan RPMJD Kabupaten.
Selain itu, sosialisasi turut membahasa alur Measurement, Analysis, and Reporting (MAR), mulai dari pengumpulan data tutupan lahan, kebakaran hutan dan lahan, Near Real Time (NRT), analisis spasial menggunakan BioCF Tools, hingga penyusunan laporan penurunan emisi. Materi mengenai Safeguard, dokumen lingkungan, serta Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM) juga disampaikan dan mendapat respon positif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para pemangku kepentingan yang hadir.
Sebagai hasil dari kegiatan ini, Pokja Kabupaten Muaro Jambi menyatakan komitmennya untuk memperkuat peran sekretariat Safeguard, Monitoring dan Evaluasi (MONEV), serta proses verifikasi proposal desa dalam mendukung implementasi RBP.
Secara keseluruhan pelaksanaan sosialisasi Program RBP BioCF-ISFL di Kabupaten Muaro Jambi berjalan lancar dan dinilai memberikan pemahaman yang lebih kuat bagi para peserta. Meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas teknis, khususnya pada aspek MAR, Safeguard, dan pemutakhiran data tutupan lahan, kegiatan ini menjadi landasan penting bagi tindak lanjut penyusunan dan verifikasi proposal RBP di tingkat Kabupaten.

Upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kehutanan dan lingkungan yang dilaksanakan di Desa Sungai Merah, Desa Pematang Kolim, dan Desa Pematang Kabau menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025 ini mencakup kegiatan Sekolah Lapang Agrofosrestri, pengembangan usaha lebah madu, serta pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD).
Di Desa Sungai Merah, kegiatan Sekolah Lapang Agroforestri pada TA 2024 menjadi sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, telah dibangung demplot agroforestri seluas 3 hektare dengan tanaman jangka panjang berupa durian dan mangga. Meski hasil ekonomi belum dapat dirasakan dalam waktu dekat karena sifat tanaman yang membutuhkan waktu tumbuh cukup lama, kegiatan ini berhasil membuka wawasan masyarkat tentang pentingnya pengelolaan lahan jangka panjang. Program tersebut diharapkan menjadi ivestasi masa depan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan pendampingan teknis dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Sementara itu, di Desa Pematang Kolim, Kelompok Tani Hutan (KTH) Pematang Kolim mendapatkan kegiatan pengembangan bisnsi berupa bantuan setup lebah madu pada TA 2025. Kegiatan ini bertujuan membuka peluang usaha baru melalui budaya lebah madu. Anggota kelompok telah memperoleh pelatihan mulai dari perawan lebah, pemberian pakan, hingga teknik pemanenan madu. Saatu ini, panen madu sudah dapat dilakukan setiap 25 hari sekali, meskipun jumlalh produksinya masih terbatas akibat sebagian koloni lebah yang kabur. Untuk mendukung pemasaran, kelompok telah menjalin kerja sama dengan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) setempat. Dari sisi kelembagaan, pembagian tugas antaranggota telah berjalan dengan baik, menunjukkan komitmen kelompok daam mengembangkan usaha madu secara berkalnjutan.
Adapun di Desa Pematang Kabau, kegiatan difokuskan pada pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas melalui kerja sama antara pihak taman nasional dan KTH Lestari. Kelompok yang berdiri sejak 2013 ini beranggotakan 23 orang dan dipimpin oleh Slamet Riyadi. Dalam pelaksanaannya, KTH Lestari berperan aktif tidak hanya dalam penanaman kembali, tetapi juga dalam produksi bibit secara mandiri. Metode yang digunakan adalah pengkayaan jenis (enrichment planting) dengan menanam jenis-jenis lokal seperti durian, alpukat, jengkol, dan rambutan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keanekaragaman hayati sekaligus memberikan potensi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekitar.
Secara keseluruhan, pelaksanaan ketiga program tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang disertai pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi masyarakaat. Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti masa tunggu panen agroforestri, rendahnya produksi madu, serta kebutuhan pemeliharaan tanaman rehabilitasi, ketiga desa memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi multipihak, program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat ekologis dan ekonomi secara berkesinambungan.